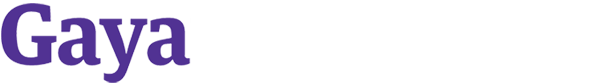MATAHARI kian bangkit, namun sekelilingku sudah riuh dengan pelbagai rutin harian penduduk kampung. Sebelum turun rumah, aku sudah lihat beberapa budak lelaki berjalan dalam kumpulan sambil ketawa. Di tangan masing-masing ada ranting kecil, sengaja memukul daun-daun hutan yang menyapa gigi jalan. Ini rutinku setiap kali pulang ke rumah tok. Kami akan menelusuri denai-denai tua yang memang langsung tidak pernah ku ambil tahu namanya, bersama tok yang kemas berbaju kurung kedah, berkain batik serta selendang hitam diselempangkan di bahu.
Sudah lama aku tidak melawat tok di kampung. Selepas Subuh, kami mencicah ubi rebus dengan gula serta menikmati kopi yang dibeli di kedai Pak Cik Wahid yang terletak dalam kampung yang sama. Kata tok, dia hendak melihat bendang yang disewakan kepada orang. Maklumlah, dia memang sudah tiada kudrat untuk mengerjakan bendang.
Tambahan pula, duit sewa bendang yang tidak seberapa itu dapat juga dijadikan wang simpanan kalau sesak. Aku tahu, setiap bulan ayah memang beri duit kepada tok melalui Mak Lang. Mak Lang tinggal tidak jauh dari rumah pusaka tok. Aku pernah dengar perbualan ayah, tok dan Mak Lang. Kata ayah, memang dia tidak mahu apa-apa tanah atau harta pusaka. Beri sahaja semua kepada adik-beradik lain kerana ayah anak sulung.
Tok berkeras juga hendak ayah memiliki tanah dusun di bukit yang terletak tidak jauh dari kampung. Mak Lang mengambil keputusan membuat rumah di tanah yang diberikan tok. Kebetulan dia dapat berpindah dari Sabah dan mengajar di sekolah rendah di simpang masuk kampung. Tok seronok bila mengetahui khabar Mak Lang dapat pindah. Namun, barangkali perkhabaran yang akan aku ceritakan kepada tok kali ini akan menggamit rasa sedihnya.
Suasana desa yang nyaman tidak cukup membuang rasa gementarku memberitahu perkhabaran ini kepada tok. Sepanjang pagi, tok memang banyak diam dan merenung. Aku cuba cari ruang bersuara.
“Tok, bulan hadapan saya akan berangkat ke luar negara.”
“Bukan kah kau sudah habis belajar? Hendak berjalan?” Walaupun usia tok mencecah sembilan puluhan, namun fikirannya cerdas.
“Saya dapat kerja di sana,”
“Di mana itu?” Tenang suara tok. “Jepun.” Jawab aku.
Terus, angin pagi dirasakan kasar menerjah muka. Tok mematikan langkah ketika kami betul-betul berada di bawah pokok asam jawa. Ketika masih anak-anak, aku takut hendak berteduh atau bermain di bawah pohon asam jawa ini. Akarnya besar sehingga timbul di permukaan tanah, mencengkam dengan kasar.
Sejujurnya, ketika kecil, mataku melihat pohon itu persis lembaga besar yang menakutkan. Daun-daunnya bagaikan lengan-lengan yang banyak dan cuba mencapai apa sahaja yang melata di sekitarnya. Bayangan tersebut kadangkala melintas di fikiranku sehingga kini.
“Di sinilah segala-galanya berlaku, Nom.” Tok menarik nafas dalam. Memejamkan mata, mengenang masa lalu yang tidak pernah terpinggir dari kotak memorinya.
“Mereka datang dengan semangat kononnya untuk membantu orang kita. Mereka datang dengan senjata dan tangan kekar yang membinasa sebahagian jiwa tok ketika itu. Ini buktinya.” Tok menuding jari telunjuknya ke arah jalan lurus dan dipenuhi belukar kecil di kiri dan kanannya. Kemudian, tok menyambung ujarannya, “Jalan yang kau harung sekarang, Nom…”
“Mereka bunuh kekuatan laki-laki yang sasa di medan silat dengan senapang dan pistol. Mereka rampas madu-madu gadis remaja dan perawan sehingga kami semua lari ketakutan, Nom…”
Aku cuba berselindung di bawah dahan-dahan asam jawa yang rendang dengan daun jarang. Tok diam membiarkan dirinya disentuh butir-butir gerimis, basah sedikit demi sedikit. Kisah tok membuatkan aku terkesima. Sungguh, tok tidak pernah beritakan aku tentang peristiwa itu. Aku semakin tidak sabar menunggu tok menyambung ceritanya.
“Mari kita pulang…”
Ketika di rumah, aku cuba membangunkan perbualan melalui omelan kecil, namun tidak bersahut. Tok memilih mengunyah sireh sambil duduk di beranda rumah. Aku menuju ke teras rumah, tempat disusun segala perabot rotan serta dilapisi selembar tikar mengkuang. Aku duduk bersimpuh di anak tangga paling atas. Menguis dedaun kering yang singgah di beranda.
“Mengapa mahu ke sana, Nom?” sederhana nada suara tok. Pandanganku penuh sinar. Aku menoleh ke arah tok.
“Tok, orang Jepun memang hebat. Mereka sangat berdisiplin dan mempunyai perkembangan teknologi yang pesat. Saya mahu bekerja di sana agar dapat mencari pekerjaan lebih baik, kelak apabila kembali ke Malaysia. Dunia memang kenal dengan kepesatan teknologi Jepun. Banyak yang dapat belajar dari mereka. Banyak…”
“Dahulunya kampung kita ini, hutan. Semuanya hutan. Penuh duri rotan dan pokok dengan akar melarat ke seluruh tanah.” Tok memang biasa bercerita kisah lampaunya dan aku sangat gemar mendengar.
“Tok masih mentah ketika itu, Nom. Namun, kami gembira. Ayah dan ibu tok bekerja mencari hasil hutan. Mereka tanam padi, menjerat burung dan anyam tikar mengkuang. Sungguh jauh sela masa untuk dikenangkan peristiwa itu, Nom. Namun, memorinya tak pernah sirna.”
“Tok pergi ke sekolah kan?”
Aku tahu tok bijak. Dia boleh membaca akhbar Melayu dan Inggeris. Bahkan, tok boleh berbahasa Jepun.
“Tok membesar dengan bendera bulat di tengah, Nom. Tok membaca bahasa dan budaya mereka untuk tunduk paras pinggang tanda hormat.” Tok menghela nafas berat.
“Jalan di seberang sana, jalan itu..” Tok menenyeh matanya yang barangkali dimasuki habuk. “Jalan itu adalah perkuburan yang menyimpan jasad-jasad rakyat yang dilupakan nama mereka. Tok masih ingat, Nom..” Tok terdiam seketika.
“Mereka paksa orang-orang itu menebas hutan sehingga cerah untuk dijadikan jalan bagi laluan tentera Jepun. Saban malam, tok mendengar kawad-kawad kaki serta herdikan sepak terajang, supaya laki-laki yang terpaksa berkorban nyawa tanpa rela itu mengerahkan tenaga seluruhnya sehingga jalan siap berturap kerikil.” Sehingga kini, tok tidak pernah menyebut nama jalan ini, kerana kenangannya sangat pahit. Aku melemparkan pandangan pada kiambang yang berdenyut abadi di jantung air dalam tempayan besar di halaman rumah.
“Nek Gayah kau lebih tersiksa jasad dan nyawanya, Nom.”
Kali ini, pandangan tok menghala ke arah telaga yang terletak kira-kira 200 meter dari rumah. Kawasan tersebut sudah semak kerana rumah tok sudah diubahsuai. Ayah sudah membelanjakan hampir sembilan puluh ribu untuk mengubahsuai rumah lama tok kepada keadaan yang lebih selesa seperti kini. Bilik tok juga dilengkapi dengan pendingin hawa. Setiap bulan ayah akan lunaskan bayaran utiliti rumah pusaka itu. Begitulah cara ayah menjaga tok dari jauh kerana kekangan kerja.
“Mengapa dengannya, tok?” Terpacul soalan dariku. Aku tidak kenal sangat Nek Gayah kerana dia agak unik. Dia akan duduk seorang diri di beranda rumah sambil tersenyum dan menyebut nama yang aku sendiri kurang fasih sebutannya. Sesuatu yang melekat dalam ingatanku tentang Nek Gayah ialah tubuhnya yang kering sering dilitupi cantik kebaya nyonya merah dan biru. Dia akan berdandan setiap kali selepas mandi dan meletakkan sekuntum bunga pada sanggul yang kian sejemput kerana faktor usia.
“Itulah kakak kandung yang tok ada. Satu-satunya kakak yang menjaga maruah diri tok sehingga mengorbankan kesucian dirinya.” Gobek yang diketuk, diletakkan perlahan-lahan di atas beranda.
“Pada malam itu, kami pulang dari kelas mengaji dari surau. Beberapa askar Jepun yang mabuk mengganggu perjalanan kami. Di tepi telaga itulah, mereka memperlakukan Nek Gayahmu seperti haiwan. Tok masih ingat jeritan Nek Gayah menyuruh tok berlari pulang. Namun, segalanya terlambat…” Nada suara tok tersekat-sekat. Aku terdiam.
“Sejak itulah Nek Gayahmu begitu. Trauma dan menggila.”
Kenangan yang digali oleh tok sungguh berat dan hangat. Aku tidak mampu berkata apa-apa. Aku tenung wajah tok yang dibesarkan melalui tanah yang meragut nyawa laki-laki tanpa dosa, keringat yang tak didendang serta maruah perawan yang dirobek tanpa belas kasihan.
Aku lihat mata bundar renta itu cuba walau sekelip untuk melupakan segala sengketa dan berlawan dengan memori, namun hampa. Bahkan, boleh dikatakan setiap malam aku akan mendengar tok meracau dalam tidurnya sambil bercakap bahasa Jepun dengan nada menghalau dan memarahi, diakhiri dengan lelehan air mata di pelipisnya yang berkedut.
Enjin kereta Mak Lang mematikan perbualan kami. Dia membawa makanan. Aku angkat semua pinggan dan makan bersama tok dan Mak Lang di beranda.
“Makanlah gulai batang pisang ini, mak.” Tok angguk. Dia menyuap nasi, disusuli meneguk air suam dalam gelas.
“Ha, makanlah, Nom. Bukan kau boleh makan gulai ini di Jepun nanti.” Aku ketawa kecil.
“Bila kau ke sana, Nom?”
“Bulan depan, Mak Lang.”
“Mak, sudah tahu Nom dapat kerja di sana?” Anggukkan tok perlahan dan tenang.
“Mestilah mak bangga, cucu pertama kerja di Jepun. Gaji mahal, mak.”
“Mahal lagi maruah negara kita, Lang.” kata tok.
Epilog 1: Aku cuba membayangkan Malaya yang masih muda politiknya pada 1942. Dihujani pelbagai doktrin dari pelbagai wilayah asing. Kini, aku sedang menghirup udara di wilayah yang pernah menjarah kematangan negara kita yang menghidupkan rasa takut rakyat Malaya zaman itu, termasuk seluruh hidup tok dan Nek Gayah.
Hokkaido menghadiahkan suasana menenangkan. Sudah menjadi rutin untukku keluar rumah dan berjalan bersama ratusan orang menuju kestinasi kerja masing-masing. Mereka langsung tidak mengangkat muka. Masing-masing melangkah bagaikan kawad kaki yang memang sudah sedia disetkan reformasinya; sama.
Sejak sebulan aku berada di sini, aku tidak lagi mempunyai kenalan yang dapat aku jadikan sandaran kerana masing-masing mengisahkan diri sendiri. Rakan-rakan di pejabatku semuanya orang lokal dan mereka sangat komited bekerja sehingga sekadar mengetahui namaku sahaja; Normah. Itupun atas dasar kerana hendak memanggilku melaksanakan tugas dengan cepat dan betul.
Sejujurnya pekerjaanku di sini sebagai pegawai yang menjaga logistik sangat memenatkan. Bangun awal pagi dan bekerja sehingga lewat malam untuk memastikan barangan tiba dengan selamat di gudang.
Ah, dan entah mengapa pada pagi itu, nyanyian tok akan lagu yang sentiasa dia nyanyikan jika berseorangan di beranda kedengaran jelas di memoriku; Miyo! Tokai no sara akete…Ya, suatu hari nanti, aku akan kembali ke tanah air dengan penuh semangat dan ilmu agar kemerdekaan yang kami kecapi kekal matang dan berisi! – MINGGUAN MALAYSIA