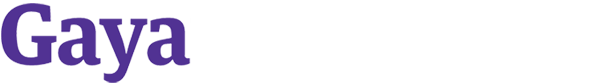MUNGKIN benar, tiada siapa yang lebih layak memikul tanggungjawab menghasilkan sebuah filem yang menggagas harapan sebagai surat cinta kepada semesta sinema Indonesia selain Garin Nugroho. Dalam deretan naskhah Garin sebelum ini, visualnya berputis, budaya, lapis kritik mencair dan menyatu menjadikannya antara sutradara paling dihormati di negara itu.
Siapa Dia selayaknya digalas Garin menceritakan tentang seorang Layar dalam hiatusnya cuba mencari rentak dan arah baru filem. Layar faham, dia tidak boleh mempersembahkan bumbu yang sama kerana penonton akan muak, jelak kerana harus menelan yang itu-itu sahaja.
Layar adalah refleksi episod ketepuan panggung yang tidak hanya terjadi kepada dunia sinema Indonesia malah di negara -negara lain termasuk Malaysia, Pakistan hingga Perancis. Ketepuan yang saya maksudnya adalah situasi di mana panggung tidak lagi berjaya menggoda penonton muda dan baru, manakala peminat sedia ada (baca: berusia) juga malas ke sana. Pendek kata, budaya menonton filem sudah berubah dan semestinya dipengaruhi banyak faktor.
Entah panggung sudah mula kehilangan makna, bergeser antara gergasi platform penstriman atau terjadinya saturation of sameness, apa yang disuguhkan oleh penggiatnya sama sahaja, tidak menawarkan kesegaran baharu buat penonton. Semua benda nampak berbeza, tapi bila ditelan semuanya terasa serupa.

Namun Siapa Dia menyisipkan pesan, segala ketepuan boleh dilawan dengan menoleh kebelakang, mengirai kenangan yang bertompok kerana antaranya terselip hikmah yang belum dirungkai. Seperti Layar, proses menjadi tukang cerita adalah perjalanan introspektif dikiaskan dengan Layar membuka beg-beg lama nenek moyang, mencari apa yang ditinggalkan. Di situlah bermulanya penggambaran kita terhadap sejarah perfileman Indonesia.
Garin mengambil jalan berani, menampilkan Siapa Dia dalam acuan muzikal bercita-cita besar. Menampilkan sejarah, drama sekali gus meminjam semangat teater yang melekat padanya. Cukup sifat untuk memberitahu penonton bahawa filem ini nyata berbeza.
Dalam menceritakan sejarah perjalanan panjang filem Indonesia yang melewati empat zaman iaitu era penjajahan Belanda, Jepun, Orde Baru dan digital, setiap zaman diwakili buyut, atuk, bapa dan Layar sendiri sebagai tukang cerita.
Sebagai penonton bukan bangsa Indonesia, ia sebuah filem pengenalan yang baik semacam penyambut tetamu di pintu yang mesra mengajak kita masuk ke dalam ruang penuh cerita. Walaupun cerita itu kemudian menetaskan kekeliruan yang bermacam-macam.
MERABA DAN MASIH TERBATA-BATA
Bagaimanapun, menampilkan sebuah filem muzikal memerlukan penelitian yang penuh kerana bermain dengan banyak komponen.
Keberkesanan filem tidak lagi hanya bergantung kepada cerita dan lakonan tetapi harus membuktikan bagaimana lagu dalam Siapa Dia mempunyai posisi kuat menyokong naratif yang diungkap. Dalam kata lain, sisi muzikal dalam naskhah ini perlu memberi makna kepada perjalanan cerita keluarga Layar.
Memandangkan Siapa Dia harus membicarakan empat zaman yang sebenarnya cukup panjang untuk disumbatkan dalam filem berdurasi 102 minit. Saya tidak menafikan, ia diceritakan sangat tergesa-gesa hingga tidak sempat pun membangun emosi juga hubungan parasosial dengan karakter utamanya.
Dengan dialog penuh kekakuan (tidak semua, hanya di zaman awal) membuatkan saya terfikir seolah-olah ini adalah naskhah dokumentari yang terperangkap dalam tubuh filem cereka. Kasihan, sudah pasti dia tersiksa.

Sepanjang tayangan, saya harus berlaku jujur dengan mengatakan walaupun lagu-lagu dalam filem ini ditampilkan dengan produksi yang cemerlang, namun ia tidak memberi nilai tambah kepada cerita. Tidak ada satu pun lagu atau babak nyanyian/ tarian yang melekat dalam kepada saya dan saya yakin, itu bukanlah disebabkan nyanyian Nicholas Saputra yang okay-okay sahaja.
Siapa Dia gagal memberikan sekurang-kurangnya satu adegan ikonik seperti Gene Kelly yang menari di bawah hujan, memegang payung dengan simbahan lampu jalan dalam Singin’ in the Rain. Juga setidaknya nuansa romantis, syahdu yang merakam melankolik yang berkesan seperti pasangan bercinta dalam La La land menerusi adegan A Lovely Night antara Sab dan Mia.
Suntikan fiksyen siri percintaan yang dilalui keturunan Layar juga tidak begitu mempersonakan walaupun menampilkan dereten syot payudara para pelakonnya. Hal seputar male gaze tidak berjaya menggoda saya. Apapun keseimbangan antara realisme dan fantasi masih dikawal kemas oleh Garin dibantu dengan ‘prop’ sesuai zamannya.
Apapun, saya percaya ada easter egg disembunyikan Garin dalam filem ini yang boleh dicermati serta dihargai peminat filem Indonesia, walaupun saya sedikit terbata-bata menduga, kerana kearifan saya terhadap filem-filem yang mereka masih biasa. Apapun, sebagai filem yang dijenamakan sebagai ‘surat cinta kepada sinema Indonesia’, semoga peminatnya akan suka.