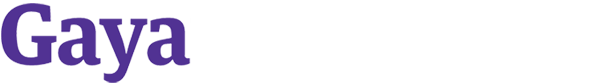“LELAKI-LELAKI mabuk kepayang hanyut, nafsu berkelana, buta mata hati. Tidak sedar neraka mendekati. Kau yang mendahagakan liuk lentuk tubuh aku ini mengkhianati perempuan kau sendiri. Lelaki dungu. Marilah aku rangkul engkau biar hangat, sehangat bara api neraka.”
Sally berdengus. Rasa jengkel tidak tertahan-tahan. Mulutnya terkumat-kamit, mata melilau mengintai dari celah-celah tabir pentas. Ruang kelab malam itu semakin sesak dengan manusia yang satu hati. Memburu syurga dunia.
Malam itu, Sally memakai gaun merah. Warna ghairah, hangat dan berahi. Sally mahu tampil begitu di hadapan pemuja-pemujanya. Menggiurkan seperti biasa, sempit baju itu mendedahkan sana sini. Potongan badan Sally 36-24-36, sempurna untuk menjadi hidangan mata lelaki-lelaki bernafsu.
Di pentas, Sally mula lincah mengalun badannya. Matanya, nakal membuatkan lelaki hidung belang yang mengelilingi pentas itu mula membuakkan khayalan. Tangan menggenggam kipas renda berwarna merah. Sesekali mengepak ke kiri, ke kanan menebarkan haruman ke pelosok kelab malam itu. Punggungnya turut bergoyang-goyang.
“Ah! Syurgaku,” kata si hidung belang bermata sepet.
“Ayuh! Sally… lagi!” Jerit seorang lelaki di hujung pentas itu. Sally mengeling
“Sabar! Abang… upahnya dulu,” lembut manja suara Sally menahan hatinya yang semakin jelik. Dia mengukir senyum sinis dari bibir merahnya yang mungil. Wang berterbangan ke atas pentas itu. Sally tersenyum lagi. Dia tahu apa yang harus dilakukan untuk mengunggah berahi lelaki-lelaki itu.
Dia kembali melentukkan badannya ke kiri ke kanan mengikut alunan muzik yang semakin memabukkan sama seperti lelaki-lelaki hidung belang itu. Tegukan demi tegukkan arak semakin mengkhayalkan mereka. Namun sosok Sally itu lebih memabukkan. Bersayap nafsu berterbangan di pelosok kelab malam itu.
Di satu sudut, seorang wanita separuh usia berkebaya merah mengulum senyum, mengenyit mata kepada Sally. Tidak sabar menantikan habuan.
Dua belas tengah malam, kelab malam itu semakin riuh. Suasana menjadi semakin kacau dengan jiwa-jiwa manusia yang semakin membara. Betapa nafsu terkinja-kinja dalam ghairah berebut-rebut dilitupi topeng munafik masing-masing. Lelaki si hidung belang makin galak mengurai kata-kata manis mengikat anak-anak gadis bermata galak yang sebaya anaknya. Untuk dibawa pulang ke ranjang malam itu.
“Sudah mabuk semuanya!” Sally berdengus lagi.
Sally menamatkan persembahannya. Dia melangkah ke belakang pentas sambil melepaskan pandangan yang mengulir dari satu sudut ke satu sudut kelab malam itu. Sekalipun bibirnya menguntum senyum namun seperti bunga kering di padang pasir di hatinya.
Sally mencium segenggam wang yang bertaburan di pentas. Wangi! Itu wangian dunia idaman Sally sejak melarikan diri dari rumah, meninggalkan kampung halaman. Dia ke hutan konkrit itu demi mengecapi kemewahan. Dosa, maksiat atau neraka tidak ada dalam kamus dirinya ketika itu.
Sally merasakan belakangnya ditepuk-tepuk. Menyentak lamunan itu.
“Makan ya. Nasi, saya ambil dari rumah transit tadi!”
Tersenyum Sally dari bibirnya yang kering merekah. Lemah badannya seakan-akan melekat pada tilam usang yang dikutipnya dari tong sampah beberapa purnama lepas. Dia masih demam. Sudah dua minggu begitu. Panas badannya membara membakar ruam yang tumbuh di seluruh tubuh yang sebahagian sudah menjadi kudis bernanah.
Sally menghantar pandangannya ketika pemuda itu berlalu dari situ. Satu-satunya pemuda yang tidak memberi pandangan menghina. Sedangkan yang lain sudah memaling dan memandang jelik.
Dua belas tengah hari. Matahari sangat terik. Sally masih tidak mampu bergerak.
Sudah enam bulan, jambatan itu kembali menjadi syurganya sejak dihalau dari rumah tumpangan tempat dia pernah berjasa kepada ibu dan bapa ayam itu.
Tiga puluh tahun, Sally menjadi primadona di tempat penuh dosa itu. Saban malam menjual dirinya dan semuanya semata-mata kerana wang. Sebahagian daripada wang itu diserahkan kepada manusia-manusia tidak sedar diuntung itu.
“Sally! Kau sudah tidak boleh tinggal di sini lagi, kau tidak membawa apa-apa hasil. Kau kena keluar,” ungkap wanita separuh usia yang masih bergetah tubuhnya. Itu ibu ayam Sally. Wanita sama mengutipnya dari bawah jambatan itu ketika dia tiba ke ibu kota.
Itu kebodohan Sally yang termakan pujuk rayu ibu ayam itu semata-mata kerana wang. Habis madu sepah dibuang. Apa lagi yang mampu diharapkan Sally, demikian kesudahan hidup manusia pendosa sepertinya.
“Aku mahu kau keluar,” bentak wanita itu lagi. Sally akur. Sally tidak berkata apa-apa. Itulah dunia menerpakan syurga atau neraka dalam sekelip mata. Dahulu, dialah pujaan ramai. Idaman lelaki mabuk kepayang. Lelaki hidung belang yang sanggup menabur ratusan wang semata-mata untuk Sally menemani mereka di ranjang.
Hari yang sama, Sally meninggalkan rumah pelacuran itu dengan hati yang luka dan berdarah. Kakinya melangkah tanpa tahu ke mana arah.
Sally berjalan lemah dalam remang senja. Senja nampak indah di mata manusia yang terluka. Bulan samar-samar di celah-celah pencakar langit. Dia berjalan ke arah bulan purnama itu. Kereta bersimpang siur bergemuruh membingitkan telinganya. Manusia tergesa-gesa seperti burung mahu pulang ke sarang. Tiada seorang pun peduli.
“Lihatlah, diri aku sekarang,” detik hati Sally. Matanya tiba-tiba panas.
Dia sedar semua kesengsaraan yang dirasainya kini adalah pembalasan dari Tuhan. Terbit daripada semua kemaksiatan dan dosa yang pernah dilakukan dahulu. Kerosakan pada tubuh badannya itu menjadi saksi. Tiada yang sihat dan elok pada pancainderanya kini.
Tangan yang merangkul ratusan lelaki semata-mata ingin memuaskan nafsu mereka kini hanya terkulai. Mata yang sering dipuji indah bak bulan penuh itu kini merah menyala. Kulit yang lembut bak baldu dahulu kini kasar, kotor penuh kudis.
Sally ingin bangkit tetapi badannya terlalu lemah. Sally masih teringat temu janji dengan seorang doktor muda berkumis halus. Waktu itu dia memberanikan diri ke hospital kerana ingin merawat sakitnya yang silih berganti. Kata doktor itu menghiris hati, membuatnya mahu hilang ingatan.
“HIV! Sally, kamu mengidap HIV.”
Itu kali terakhir Sally merasa sebagai manusia kerana hari-hari selepas itu hanya seperti mayat hidup. Otot sendinya semakin perit. Ruam pada seluruh badan bertukar menjadi kudis sehingga menjijikkan mata memandang. Kesakitan itu yang menghantar Sally kembali ke bawah jambatan itu. Kerana itu sahaja tempat yang mahu menerimanya.
Teman-teman rumah tumpangan yang menjadi tempat sama-sama bergelak ketawa sudah menghilang. Tiada siapa lagi untuknya. Mahu pulang ke kampung, 30 tahun bukan singkat untuk keluarganya memaafkan dirinya yang meninggalkan mereka begitu sahaja dahulu.
Hati Sally kembali tersayat dengan kenangan pahit itu merobek-robek sehingga ke jantung, lebih perit dari luka-luka bernanah di tubuhnya.
“Dasar manusia tidak sedar diri.” Sally kesal.
“Pemuda! pemuda! Tolong aku ambilkan air. Aku mahu solat Zuhur.”
Lemah teriakan Sally kepada anak muda yang sibuk menghantar bungkusan nasi dari satu ke satu orang tanpa rumah itu. Anak muda berwajah polos ini hanya tersenyum. Mendekati Sally sambil menghulurkan sebotol air mineral dan berlalu.
Sally hilang waktu, namun alunan azan dari kubah masjid berdekatan dengan jambatan itu menjadi pengingat lima waktunya.
“Hari ini, hari Jumaat,” Sally berbisik kepada dirinya sendiri. Sally tahu kerana dia sudah terbiasa dengan hiruk pikuk manusia lalu lalang di atas jambatan itu untuk ke masjid. Sally benar-benar lemah. Badannya semakin panas. Tiada dirasai biasa seperti selalu.
Selesai solat, Sally berdoa, berzikir dan bertasbih sambil terbaring menghadap kiblat dengan mata berkaca. Dia memohon Tuhan mengampunkan semua dosanya.
Sally kembali sujud kepada Sang Pencipta sejak kembali ke bawah jambatan itu. Malu hatinya pada Tuhan yang sudah lama dilupakan itu.
Nun, di barat matahari merendah. Langit merekah berona jingga. Melekat pandangan Sally menghantar matahari pulang untuk menyambut senja. Senja yang merangkumi hati-hati yang sedih. Hati Sally sedih. Sayu entah kenapa berlebihan pada penghujung siang hari itu.
Bulan. Pungguk. Semilir angin mula berhembus riang, nyamuk pun terbang gembira. Manusia-manusia tanpa rumah itu kembali mengerumuni bawah jambatan itu. Menderu mencari sudut untuk melabuhkan badan. Mereka semua orang-orang patah hati, hidup sekadar menunggu mati.
Bulan kelihatan bersinar pada permukaan sungai itu.Sally tiba-tiba mendengarnya namanya diseru.
“Salim! Salim!”
Buat sesekian lama, Sally kembali mendengar nama itu. Nama itu tiba-tiba terasa indah di telinganya. Rindu. Namun jantungnya berdetak kencang, gementarnya bukan kepalang, bulu romanya tiba-tiba meremang.
“Salim!” Seruan itu semakin dekat. Bayangan itu semakin rapat.
Sally tersenyum kerana dia memahami pemilik suara di sebalik bayangan itu. Sally tidak takut lagi.
Nafas Sally semakin tersekat-sekat. Sakitnya berhujam jiwa dan menyebar ke seluruh anggota badan. Bagai ditarik-tarik, dicabut-cabut dirinya dari setiap urat nadi, urat saraf, dari setiap akar rambut sehingga kulit kepala hingga ke kaki.
“Allah! Ampunkan dosa aku.” Sally mengucap dengan nada tersekat-sekat namun sempurna. Matanya pedih dan tekaknya makin perit. Pada kala mata yang semakin berkaca itu Sally terpandang bayang di permukaan sungai yang tenang.
Wajah seorang wanita memeluk seorang budak perempuan seolah-olah melambai pergi kepadanya. Mereka tersenyum. Mata Sally semakin panas … Kabur. Nafasnya semakin berat
“Maafkan abang! Maafkan ayah!
Bulan semakin terang terendam di dalam air menghilangkan wajah-wajah suram itu dari pandangan Sally. – Mingguan Malaysia