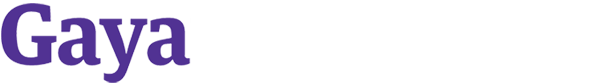Karya Zalina Samsudin
Tus! Tus!
Ada titis-titis air jatuh dari langit lalu mendarat di atas atap. Gumpalan awan kelabu tengah hari kelihatan berat benar.
Tus! Tus! Tus!
Detak-detak tengkujuh menggetar jiwa. Azira berpaling ke dapur. Pandangan memusat ke sudut rumah yang tiris. Riak-riak bimbang berserakan. Rezeki belum dijamah. Harap-harap langit mampu bertahan.
Di ambang pintu Azira duduk bersimpuh. Sebagaimana tertib seorang wanita Melayu. Dia memandang semula tetamu yang jarang-jarang mahu melangkah melepasi bendul rumah. Tetamu yang memang sejak dari dahulu seperti tidak sudi untuk memijak teratak kayu buruknya. Dua rentak hidup yang berbeza, barangkali itulah jawapan.
Tus! Tus! Tus! Tus!
Sabar langit ada hadnya. Bila-bila masa akan runtuh.
“Aku balik dulu. Kau ada masa seminggu. Fikir masak-masak. Bukan senang nak dapat tawaran yang tinggi. Sekali ini saja.”
Tetamu itu tergocoh-gocoh meranduk halaman yang becak. Percik-percik lumpur memalit corak di kaki seluar namun tidak sedikit pun diendahkan. Lumpur yang berpercikan itu hanyalah hal remeh. Dalam kepala, ada banyak perkara lebih penting untuk difikirkan.
Tanpa ucapan, salam atau selamat misalnya, Azira dibius bisu. Masa? Bukan sekali dua Amar memberi tempoh masa. Sudah tiada beza pemberian kali ini berbanding sebelumnya. Dia pun tidak pernah mengambil masa yang diberi. Dia tiada masa untuk memikirkan semua itu.
Keputusan sudah lama muktamad. Tiada sebarang kompromi lagi. Hanya Amar yang masih menagih persetujuan. Kalau-kalau hati perempuannya lembut dan beralih pegangan.
Azira menutup pintu. Dia tidak mendengar titisan lagi. Barangkali hujan tadi hujan lari. Dia berterima kasih pada hujan yang berlalu pergi. Jika tidak entah apa lagi tawaran manis meniti di bibir Amar.
“Ila, goreng ikan masin!”
Anak kedua menurut arahan. Kuali, sudip dan minyak berdendangan. Sebenarnya memang itu yang Azira mahu lakukan kurang setengah jam lalu. Kunjungan Amar membantutkan segala.
Harap-harap sempat. Sekarang bukan boleh berjanji dengan cuaca. Hujan yang lari pasti kembali semula. Bila-bila masa mengikut keadaan. Mereka perlu menyegerakan santapan tengah hari. Jika tidak dapur itu akan kebanjiran air hujan. Azira tidak mahu air hujan menjadi perisa tambahan di dalam pinggan rezeki.
Aroma ikan masin bertebaran ke segenap ruang. Teratak kayu itu pun bukan besar tetapi selesa. Kecil tidak mengapa asalkan dipenuhi kasih sayang.
Gulai lemak pucuk ubi bersama ikan keli salai sudah terhidang. Tidak ketinggalan sambal belacan dan ulam raja. Sepiring kecil ikan masin menjadi pelengkap hidangan. Mereka menikmatinya penuh selera, seberapa segera.
“Mak nak terima?”
Mulut bertanya tetapi mata tertumpu ke permukaan meja. Ila mengelap remah-remah makanan. Anak dara itu kelihatan bersungguh-sungguh, seakan mahu menyapu semua kebimbangan bersama perca kain batik lusuh yang digunakan.
“Berapapun tawarannya, tetap tidak. Ini hak kita!”
Jawapan yang tegas. Azira tahu takkan selamanya Ila mengunci soalan itu. Dia memang sudah bersedia menjawab. Dahulu, kini… selamanya, itulah jawapan. Tiada perubahan.
Suasana senyap. Baik si penanya mahupun si penjawab pertanyaan, kedua-duanya menyimpan suara. Soalan itu memang menyakitkan. Usah dipanjangkan lagi. Kalau boleh, jangan ada sesiapa pun yang membangkitkannya.
Tiba-tiba senyap itu diganti dengan dentam-dentum. Di luar jendela, langit kelabu kehitaman. Sudah terlalu berat bebanan yang ditampung.
“Cepat pergi tengok kain baju. Yang kering, yang kering-kering air semua angkat. Jemur dalam rumah.”
Ila mematuhi arahan lantas berkejaran ke ampaian. Sepanjang pagi ada bayang-bayang mentari yang kelihatan selepas tiga hari hujan turun tidak henti-henti. Kalau yang basah itu bertukar lembap pun jadilah.
Santapan tengah hari selesai. Dapur sudah kemas. Pakaian siap diangkat. Ya awan, andai tidak tertanggung lagi lepaskanlah…
Seakan awan mendengar, beban tertampung terlepas jua. Seperti sabar sudah tiada, langit dan awan sama-sama meraung.
Azira mengerling ke atap yang ketirisan. Air jernih sebesar lidi pencucuk sate meluncur jatuh. Maka tirislah juga batin dan raga. Dia mengambil besen. Buat penadah air yang menitik ke lantai. Selagi mana besen itu mampu menadah, maka menadahlah. Dia sedar sekejap lagi airnya akan melimpah.
Di luar sana, ada yang lebih membuatkan dirinya walang. Azira memandang sungai berjarak 300 meter dari teratak kecilnya. Air berubah menjadi warna teh tarik sebermula musim tengkujuh dua minggu lalu.
Pagi tadi sewaktu hendak pergi kerja, tebingnya belum ampuh. Sekarang sudah sekaki melepasi tebing. Ditambah hujan lebat, air pasti naik lagi. Apalah ada pada daya. Walang berterusan menjadi keluh kesah.
Tempias-tempias hujan singgah di muka. Azira menarik dedaun jendela. Tatkala separa tertutup, terpandang pula anak pokok buah-buahan yang berjajaran di tanah bersebelahan. Seakan ternampak-nampak Amar berlegaran di situ. Rasa sakit hati pun menyerang. Dia cepat-cepat mengatup jendela. Amar dan amarah turut padam.
Besen penadah sudah penuh. Tiada apa yang mampu menghalang. Biarkanlah. Nampaknya esok Azira perlu cari Hamid. Musim tengkujuh masih panjang. Beli atap baharu dan ganti atap lama, segala urusan akan diserahkan kepada tukang rumah itu.
Kalau dengan Hamid boleh runding-runding. Dia pun bukan berkira sangat orangnya. Kerja baik pulih yang kecil-kecil, memang dialah pilihan warga desa.
Dua jam sudah berlalu. Hujan pun sebegitulah juga. Tetap lebat seperti mula-mula mencecah bumi. Ecah dan Poji merengek kelaparan. Biasalah. Hari sejuk, perut pasti berkeroncong. Azira ke dapur. Dia tidak peduli dapur itu banjir, basah atau apapun. Dia hanya mahu anak-anaknya kenyang.
Azira merebus ubi kayu. Bekalan ubi kayu baru digali ada seguni. Secerek air tertenggek di atas dapur. Sambil-sambil menanti ubi dan air masak, dia periksa almari lauk. Sekampit kecil beras, tepung, gula dan kopi, semuanya tersedia. Ikan masin dan ikan pekasam juga ada.
Pesan Iskandar supaya bekalan makanan itu sentiasa tersedia sepanjang tengkujuh tetap dia ingat meskipun sudah lima tahun ketiadaannya.
Bekalan sayur kampung pula subur di sekeliling rumah. Bila perlu petik sahaja, tiada masalah. Selain makan sendiri, dia tumpang jual di warung kopi Mak Besah, tempat mencari rezeki hari-hari. Lepaslah untuk beli lauk.
Azira buka jendela dapur. Air semakin naik. Sedang hujan seakan hilang belas ihsan. Dalam pada bermenung-menung di jendela, ubi dan air pun masak. Dia lempar semua kebimbangan. Biarkan air hujan di luar sama membasuh semuanya. Perut yang kosong perlu diisi dahulu.
Tiga jam kemudian, pendirian hujan masih teguh. Gelap melayah kunjungan. Jika cuaca baik, azan maghrib berkumandang sayup-sayup dari masjid kampungnya. Tetapi senja ini Azira tidak mendengar apa-apa selain raungan langit. Dia jeling jam yang melekap di dinding. Sudah masuk waktu maghrib.
Azira buka lagi jendela. Entah kali yang keberapa sepanjang hari ini. Bah sudah menggenangi halaman belakang. Dia suruh anak-anak bersolat. Dia juga pesan pada mereka sesudah solat, panjatkan doa setulusnya. Moga-moga mereka terhindar daripada sebarang musibah.
“Kita kena pindah ke pondok durian Ayah Talib malam ni juga.”
Tiada tangguh-tangguh. Seusai solat, mereka mengemas apa yang patut. Azira turun ke dapur. Bah sudah beberapa inci menenggelamkan lantai. Dia buka almari lauk dan ambil bekalan makanan. Semuanya dia bungkus dalam beg plastik.
Di ruang tamu, anak-anak sudah bersedia dengan beg sekolah. Azira periksa dokumen penting satu-persatu. Semuanya lengkap. Keselamatan nyawa menjadi keutamaan. Dia minta Edi segera mengambil motor kapcai pusaka ayahnya.
Azira letak bungkusan plastik yang berisi bekalan makanan di dalam raga motor. Kemudian dia bergegas ke dapur sekali lagi. Seguni ubi kayu dipikul tanpa ada rasa berat. Mengenangkan perut anak-anak, kekuatan datang sendiri.
Lima beranak itu meredah hujan lebat. Berbekalkan cahaya lampu suluh, mereka mendaki bukit menuju ke pondok durian. Letaknya tidak berapa jauh dari teratak kecil mereka.
Tubuh habis lencun. Azira mengarahkan anak-anaknya menukar pakaian. Dia bimbang mereka demam terutama Poji yang masih kecil.
“Kambing dan ayam kita macam mana mak?”
Ya tak ya juga. Azira terlupa akan kambing di kandang. Juga ayam peliharaan. Kalau rumah tenggelam, kandang dan reban pasti tenggelam. Dia tidak sampai hati. Bukankah haiwan-haiwan itu sebahagian daripada keluarga mereka dan perlu diselamatkan juga.
“Ila jaga adik-adik. Mak dan abang nak turun bawah lepaskan kambing dan ayam.”
Azira dan anak sulungnya menuruni bukit semula. Entah macam mana dia terjatuh. Edi yang mendahului lima langkah di depan berpatah balik.
“Mak tak apa-apa. Cepat, air makin naik!”
Azira berbohong. Mustahil tidak sakit jikalau lutut terhantuk akar kayu. Dia tidak mahu beritahu perihal itu. Waktu terus mengejar. Perlahan-lahan dia bangun dan cuba menapak. Boleh, walaupun terhincut-hincut.
Azira suluh reban ayam. Air sudah sejengkal melepasi tiang. Edi buka pintu dan ketuk dinding reban. Ayam-ayam kegemparan. Edi ketuk lagi. Semua bertempiaran keluar.
“Naik ke darat semua. Pandai-pandailah cari tempat tidur!”
Azira memekik seolah-olah ayam itu faham. Seekor demi seekor hilang ditelan pekat malam. Mereka beralih ke kandang kambing. Edi tarik Abang Janggut, kambing jantan yang paling besar. Yang lain turut mengikut. Mereka berjujukan menuju ke bukit.
Sepanjang malam langit sekejap-sekejap meraung, sekejap-sekejap kesenduan. Di bawah bukit, Azira mendengar bah mengamuk. Menderu-deru. Membuak-buak. Dia tidak mampu melelapkan mata. Dia cuba bertenang, ditemani cahaya lilin yang meliuk-liuk. Sebarang kemungkinan yang terjadi, dia perlu bersedia menerimanya.
Sedar tak sedar dinihari muncul. Azira mendengar kokokan Merah, ayam jantan kesayangan. Hatinya sedikit lega. Kalau Merah selamat, tentu ayam-ayam lain selamat juga. Harap-harap Abang Janggut dan kambing sekandang pun sama.
Langit sudah tenang. Meninggalkan kedinginan yang menggigit tulang. Laungan azan sayup-menyayup. Anak-anak yang masih ketiduran dikejutkan. Selesai melunaskan kewajiban, Azira menelefon Mak Besah. Kepadanya diluahkan segala yang berlaku.
Terang sahaja tanah, mereka turun meninjau keadaan. Azira terduduk kepiluan. Separuh nyawa seakan melayang. Edi menelan kata-kata. Ila pula menyulam air mata. Segala-galanya lenyap. Bah menyapu semua milik mereka.
Ayah Talib, suami Mak Besah tiba. Amar menyusul seminit kemudian. Lelaki itu mencangkung, menghadap dusunnya yang musnah. Yang kelihatan hanyalah lumpur dan reja-reja kayu. Suku daripada tebing tanahnya terhakis, hanyut dibawa arus.
Lihat Amar. Adakah ini dinamakan taman ekopelancongan yang sering kau banggakan?
Di mana akan kau dirikan chalet-chalet idaman? Di tebing yang longgar itukah? Tawaran puluhan ribu yang kau janji, sepadankah dengan nilai kemusnahan yang berlaku? Azira mahu berteriak, meluahkan segala tetapi rasa hormat masih ada.
Amar abang kepada arwah suaminya. Perasaan marah itu membara tetapi dia tidak mahu mengajar anak-anaknya menjadi kurang ajar terutama darah daging sendiri. Biar miskin harta jangan miskin budi bahasa.
Azira akur, alam sudah menang. Dia menyerah kalah tetapi kekalahannya bermaruah. Namun antara dia dan Amar, mereka sama-sama seri.
Hujan rebas-rebas lagi. Melunturkan ketenangan sang pagi. – Mingguan Malaysia