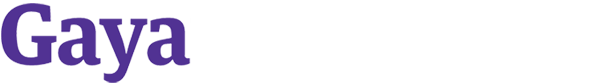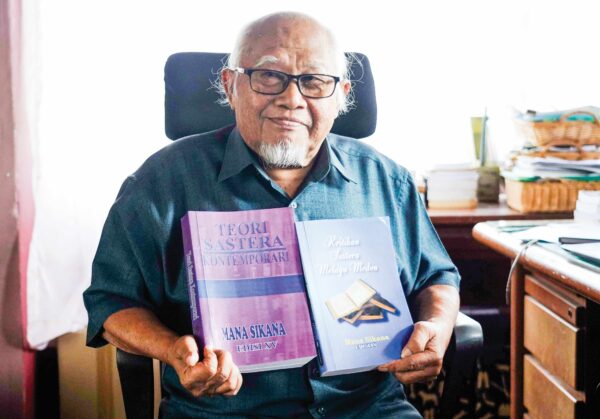Semua penduduk kampung itu berkumpul. Tidak ada seorang pun berkecuali. Kemudian ketua kampung yang tua renta itu berdiri di antara mereka lalu berkata, “Saya sedang mengarang buku, belum sempat habis saya tulis, buku itu hilang. Saya sangat sayangkan buku agama saya itu. Buku itu mengenai cara-cara sembahyang malam yang sempurna. Tolonglah carikan buku itu. Saya akan berikan hadiah besar sesiapa yang menjumpainya.” Katanya tergagap-gagap.
Terpinga-pinga penduduk kampung itu. Mereka fikirkan apakah amanat yang hendak disampaikan. Atau adakah lagi pembesar negeri yang datang, berapa ekor lembu yang harus dikorbankan. Rupa-rupanya tentang buku yang hilang. Namun, mereka harus taat kepada ketua ini.
“Bagaimana buku itu, Tok Ketua?” Tanya seorang anak muda.
“Seperti biasa, semacam buku”.
“Apa isinya?” Tanya pemuda itu lagi ingin tahu.
“Isinya sangat menarik. Tidak pernah saya menulis sebegitu sungguh-sungguh.”
Mendengar jawapan itu, anak muda itu tersenyum. Bergegas dia kembali ke rumahnya yang tidak jauh dari situ, dan kemudian dia mengambil sebuah buku daripada almari rumahnya. Sambil berlari dia berkata kepada semua orang yang sedang keletihan mencari buku itu.
“Saya dah jumpa buku itu, dah jumpa,” katanya sambil mengangkat-ngangkat buku tersebut bagaikan mengebar-ngebarkan sebuah bendera.
Semua orang tertumpu kepada buku itu. Dan mereka semuanya kelihatan lega.
Bersinar-sinar mata ketua kampung. Wajahnya pun berseri. Akhirnya dia bertemu juga dengan buku yang hilang itu. Dengan segera dia mendapatkan pemuda itu. Tidak cepat pemuda itu menunjukkan buku itu kepada ketua kampung itu; sebaliknya dia membelek-belek isi buku itu. Kemudian baru diserahkannya.
Ketua kampung itu menyambutnya gembira. Menatap-natap dan membuka-buka buku itu. “Ini bukan bukunya.” Kataya dengan kuat.
Penduduk kampung itu kembali dalam keadaan resah. Lagi gelisah. Selagi buku itu tidak diketemui, selagi itu ketua kampung itu bikin ribut. Itulah bezanya nasib ketua kampung dengan penduduk kampung. Suatu masa dahulu, ada penduduk kampung kehilangan kambing, tidak dipedulikan pun. Tiba-tiba dijumpai kambing itu masuk ke dalam telaga. Dan, tidak ada siapa yang mahu membantu mengangkat kambing itu ke atas.
Ini hanya hilang sebuah buku. Hairan juga. Bagaimana dikatakan buku, pun belum selesai ditulis. Yang sebenarnya ia adalah sebuah manuskrip. Oleh kerana ketua kampung itu menyebutnya sebagai buku, maka bukulah. Tidak ada siapa yang berani menyoalnya.
Berita kehilangan buku itu sampai kekampung jiran. Masing-masing berusaha membantu mencarikan buku agama yang hilang itu. Seorang penduduk yang dianggap sangat tua, hidup bersendirian dan sedikit absurd, menyatakan dia ada menemui buku itu. Masing-masing mahu memastikan, apakah itu benar buku yang hilang itu. Buku itu pun kelihatan sudah sangat tua. Lusuh. Sudah hilang kulitnya.
“Ha ha ha ….” tiba-tiba seorang anak muda yang membelek-belek buku itu, ketawa terbahak-bahak, sekuat-kuatnya. “Ini buku Thus Spoke Zarathustra tulisan Friedrich Nietzsche,” sambung anak muda seorang mahasiswa fakulti falsafah.
Penduduk kampung juga ketawa terbahak-bahak. Walaupun sebenarnya mereka tidak faham apa yang dikatakan oleh budak universiti itu.
Penduduk kampung itu benar-benar dalam depresi. Id mereka sudah dikalahkan oleh libido yang menguasai seluruh super-ego mereka. Bawah sedar mereka sudah ditawan.
Jika ada sesuatu berita tentang penemuan buku itu, tentu sahaja amat menggembirakan. Begitulah tiba-tiba sahaja penduduk kampung itu sangat gembira, kerana telah menemui buku yang hilang itu. Ketua kampung telah ditunjukkan isi kandungannya. Tersenyum sahaja. Semua penduduk kampung pun turut tersenyum. Mereka tidak perlu lagi tercari-cari.
“Apakah isinya?”
“Cuba kau bacakan. Ingin juga nak tahu apa isinya!”
“Nampaknya agak panjang juga,” kata pemuda yang menemui buku itu, dia bersedia untuk membaca, justeru begitu ramai orang kampung yang ingin mendengarnya.
Ada dua orang yang sama tarikh lahirnya. Bukan sahaja sama harinya, bulannya, tahunnya, jamnya, dan saatnya pun sama. Nama pun diberi oleh keluarga masing-masing bermula dengan Abu, seorang bernama Abu Bakar, seorang lagi Abu Bakir. Kedua-dua keluarga itu memanggilnya dengan nama Abu. Untuk membezakannya penduduk daerah itu memanggilnya dengan nama Abakar dan Abakir.
Namun, kedua-dua mempunyai perbezaan daripada segi agama. Keluarga Abakar, ayahnya imam di surau kampung itu, sedang ayah Abakir langsung tidak bersekolah, dan jahiliyah pula. Bagaimana pun, sebagai seorang imam, si ayah mahu anaknya Si Abakar, menjadi anak beragama; tetapi Abakar ini, agak culas orangnya. Apabila disuruh sembahyang ketat tulangnya. Kadang-kadang bila ditanya, dia akan berkata, “saya dah sembahyang, ayah.”
Abakir lain pula, dia seorang yang taat pada agama. Pun belajar daripada imam surau daerahnya itu, ayah Abakar. Sembahyangnya pun tidak tinggal, meski dia sedang meremaja.
Abakar dan Abakir bersekolah yang sama. Sama kelas dan sama berkembang. Cuma Abakar, meski dia kelihatan agak nakal, dia cerdik dan pintar. Sementara Abakir agak lembap dan sedikit malas. Kedua-duanya terkenal sebagai pelajar yang rajin membaca. Kedua-duanya pun akhirnya minat dalam dunia kepengarangan. Abakar menulis puisi. Abakir menulis cerpen. Namun, nasib kedua-duanya agak berbeza, Abakar sering mendapat hadiah, kerana kekuatan dan keindahan puisinya. Sementara Abakir, cerpennya mediocre saja, tidak pernah mendapat sebarang hadiah atau penghargaan. Daripada sinilah kedua-dua sahabat ini mula berselisih jalan.
“Zaman sekarang bukan zaman sajak lagi. Zaman sajak adalah zaman romantisisme, zaman yang sudah berlalu.” Kata Abakir cuba menyindir.
“Cerpen kau kudengar orang tak faham. Kau terlalu sangat bermain lambang,” balas Abakar. Sinis.
“Siapa yang banyak bermain lambang, sajak kau atau cerpenku?”
Waktu itu sebenarnya kedua-duanya sedang bersekolah menengah, dan akan menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia. Dan ternyata Abakar lebih menguasai ilmu sastera, kerana dia mengambil mata pelajaran sastera elektif Kesusasteraan Melayu; sedangkan Abakir mengambil Asas Perakaunan.
Begitulah mereka masuk ke universiti yang sama. Seorang di Fakulti Kesusasteraan. Seorang lagi di Fakulti Ekonomi. Sementara Abakir hanya sebagai pelajar biasa saja. Abakar menganut aliran humanisme, sajakn-sajaknya menyuarakan kemanusiaaan. Abakir pula meneruskan menulis cerpen-cerpen Islam, yang berlambang, yang remang dan keabsurdan.
Universiti itu sememangnya dua tahun sekali akan mengadakan majlis penyampaian Hadiah Sastera. Kedua-dua juga diisytihar sebagai pemenang. Seorang genre puisi dan seorang lagi dalam genre prosa. Anehnya, Abakir yang menang kerana cerpennya, yang dianggap oleh panel luar biasa mendekati gaya Alain Robbe-Grillet, pengarang Perancis yang tersohor itu, dia tidak mahu menerima anugerah itu. Punca ialah dia mendengar Abakar ada memberitahu orang, bahawa cerpen itu, semacam suatu peniruan daripada teks pengarang Barat itu.
“Kau salah faham, Abakir.”
“Apa pula kau yang hebahkan pada pelajar semua, kononnya aku ni menciplak.”
“Siapa kata, aku kata kau menciplak? Siapa?”
“Aku tahu kau memang dengki dengan cerpen-cerpen aku. Hei, aku belajar tahu, bagaimana nak tulis teks-teks macam tu. Aku bukan menciplak!” Abakir nampaknya meninggikan suaranya. Amarah dan nekad.
Abakar tersenyum,”dengar sini, aku tak kata menciplak, aku hanya kata kau memparodi.”
“Parodi?” Suara Abakir menunjukkan dia tidak pernah mendengar perkataan itu.
“Apabila kita menggunakan sebuah teks lain sebagai model, kita ubah, kita transformasi atau modifikasi, atau kita tokoh-tambah, itu namanya parodi atau intertekstualiti…”
Belum habis lagi, Abakir menyampuk, terkilan, “ah, nampaknya benda tu macam ciplak juga, sebab itu pelajar-pelajar kata aku ciplak.”
Masing-masing terus mengembangkan diri dalam penulisan. Dan sesuatu yang menarik, kerana kedua-duanya mendapat disiplin ilmu di universiti, kedua-dua menulis esei. Ada perbezaan daripada sudut pandangan dan tujahan kedua-duanya. Abakar lebih berminat mengkaji dan penyelediki sastera Melayu daripada akar tradisinya.
“Pantun telah diterima sebagai sumbangan terbesar zaman sastera rakyat. Telah dipersetujui umum, bahawa pantun adalah ciptaan asli orang Melayu, ia bukan saduran atau penyesuaian daripada puisi-puisi Jawa, India, Cina dan sebagainya. Sifatnya sebagai sastera rakyat dan bentuknya yang dalam empat baris, quatrain, menyatakan sesuatu fikiran yang bulat dan lengkap.” Demikian tulis Abakar dalam sebuah eseinya.
Sementara Abakar pula banyak membicarakan Islam dan apabila membahaskan sastera, dia akan bincangkan sastera Islam. Antara lain dia pernah menulis. “Ke manakah arah penulis Islam sekarang? Pertanyaan itu membayangkan kemungkinan para penulis Islam mutakhir tidak mengenal atau mengetahui cabaran perdana dan keperluan yang harus dihadapi di zaman pascamodenisme ini. Sesungguhnya cabaran dan tanggungjawab para penulis sekarang tidak sama dengan zaman modenisme; cabarannya juga lebih sengit dan tajam lalu menuntut penglibatan yang total daripada kalangan para penulis Islam”.
Begitulah dua sahabat, sekampung, dan yang penting sesaat masa kelahiran itu, telah memilih jalan masing-masing. Abakar telah mendapat kelas pertama dalam ijazah sarjana mudanya. Abakir hanya lulus cukup-cukup makan sahaja. Abakar berpeluang melanjutkan pelajarannya di peringkat ijazah sarjana. Meski pun dia terkenal sebagai seorang penyair, tetapi bidang kajiannya bukan genre puisi, sebaliknya dia lebih berminat dalam bidang teori sastera.
Begitulah dihikayatkan pertempuran antara kedua tokoh sastera yang lahir sama tahun, bulan, hari dan saat ini terus berlanjutan. Kata orang, sampai mereka tua, cukup tua, gigi pun rentuk, mata pun rabun, malah sudah nyanyuk, perkelahian keduanya tidak pernah selesai.
“Itulah isi buku itu,” kata pemuda itu menamatkan bacaannya. Kelihatan dia berpeluh dan penat juga dia membaca buku itu.
Ketua kampung sedikit terbelalak matanya. “Memang itu buku aku, daripada kumpulan cerpen ke sepuluhku, tetapi bukan buku yang hilang itu.”
Kenyataan itu membuat semua penduduk kampung itu terbelalak lagi. Juga hampa. Bagaimana pun kemudian mereka bersurai. Yang tinggal hanya pemuda itu masih tercegat kehairanan. Dia sudah menemui dan membacanya agak panjang, sayangnya dinyatakan itu bukannya buku yang hilang itu. Hairan!
“Apa yang dihairankan,” tiba-tiba muncul seorang anak muda lain, sambil dia memegang bahu anak muda yang tercegat itu.” Aku telah jumpa buku hilang itu. Ia bukan buku tentang sastera, juga bukan tentang agama”.
“Di mana kamu jumpa bukuku itu?” Ketua kampung gembira tetapi masih dalam tanda tanya.
“Tersimpan dalam belukar. Ada tanda-tanda buku ini telah dibaca ramai penduduk kampung. Termasuk anak-anak muda.”
“Ironik sekali. Ajaib. Juga sebuah alegori.” Kata pemuda yang masih dalam kehairanan.
Ketua kampung tersengih. Membeleknya. Memang benar itulah bukunya.
Kata pemuda yang menemui buku itu, “Buku ini ialah cara-cara mengadap hari pertama perkahwinan. Menarik dan seronok. Penuh ghairah.” Ketua kampung yang tua renta itu tersenyum. – Mingguan Malaysia