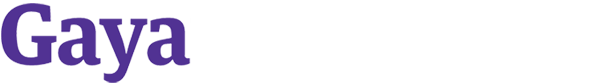“Busuk, hitam,” ejek Suri, anak Pak Leman, tauke kedai di hujung jalan Kampung Sendora.
Aliff menghela nafas panjang. “Huh!” bentak hati pemuda berkulit hitam manis, bertubuh kurus kering, berambut keriting itu.
Bagai mahu ditelan. Bulat mata Suri memandang Aliff sebelum memaling mukanya. Suri belum puas, sekonyong-konyong tangan putih gebunya memulas minyak motosikal Honda kapcai itu berkali-kali. Sengaja dibiarkan Aliff menghidu kepulan asap dari corong ekzos motosikalnya.
“Padan muka!” jerit Suri. Besar ketawanya. Tetapi pemuda itu bagai terkesima. Ketawa Suri itu tetap terdengar indah di halwa telinganya. Punggung Aliff masih terpaku pada tebing di parit gila itu. Memujuk rasa. Pedih mata Aliff menahan asap motosikal Suri. Tetapi pedih lagi hatinya.
Andai lelaki dibenarkan menangis, dia sudah lama meraung namun tangisan dalam hatinya sudah lama bersarang. Dek penghinaan demi penghinaan daripada gadis pujaan hatinya itu.
Hinaan itu tidak pernah melemahkan cinta Aliff pada Suri. Saban malam dia masih bermimpi untuk menyunting gadis itu menjadi suri dalam hidupnya. Walaupun dia sedar, keinginan itu hanya kepalsuan yang dibiarkan membuai hatinya yang sunyi. Aliff juga sedar, dia dan parit gila itu sama sahaja. Miliki seribu kegunaan tetapi tidak akan pernah dipandang jasanya.
“Adik… adik… turun makan,” panggilan Mak Milah mengertak lamunan Aliff.
Hatinya masih sakit masakan dapat menjamah sebutir nasi pun.
“Tak guna… Penipu!” dengus Aliff. Tangannya tidak semena-mena melontarkan sebekas Pomade yang baru dibelinya di pekan nat Kampung Sendora, kelmarin. Nyata dia termakan pujukan penjual itu. “Adik, pakai ini. Awek tentu suka. Sapu-sapu segak,” pujuk tukang jual itu. Aliff hanya tersenyum, dia hanya terbayang Suri. Tentu Suri akan tertawan. Pomade yang trending ketika ini. Hati Aliff cukup berbunga apabila mengoles Pomade ke rambutnya usai Subuh tadi. Ketika fajar mula memijar, Aliff sudah terpacak di parit gila itu. Tertinjau-tinjau kelibat Suri yang saban pagi melalui batas parit gila itu ke pasar. Nyata hatinya, hampa lagi.
“Buruk benar ke muka aku,” hati Aliff berdetik lagi. Memandang cermin usang di hujung katil bujang itu. Mak Milah selalu memujinya, “Anak mak ini segak macam ayah dulu-dulu.”
“Ah,” dihempaskan badannya yang kurus kering itu ke katil bujang itu. Malas.
“Adik! Adik! Turun makan,” suara ibunya semakin kuat.
“Ya! Allah, Adik kenapa bersepah ni. Jom makan mak masak ayam masak lemak, Aliff suka, kan?” Lembut sahaja suara wanita separuh umur ini yang terpacul di hadapan biliknya.
“Tak apalah, mak. Nanti orang makan,” jawab Aliff. Hati masih meradang.
“Aliff nak makan dengan ayah ya,” tenang wanita itu tidak mahu memaksa sebelum berlalu dari situ. Namun dia tahu anak bujangnya itu sedang bersedih.
Mendengarkan perkataan ayah itu sudah membuatkan hati Aliff bertambah sakit. Telinganya masih panas dek terkena tamparan Pak Ali minggu lepas.
“Kalau adik ke Pulau Pinang, siapa nak jaga bendang kita. Nak biarkan ayah seorang?”
“Orang tak mahu buat bendang dah. Orang nak kerja kilang ikut kawan-kawan. Orang penat ayah. Orang ada impian orang juga.”
“Tak boleh! Ayah sudah tak larat. Kalau adik tak tolong, siapa lagi?”
“Orang tak kira orang nak pergi juga cukup bulan ini.”
“Kalau adik nak pergi juga, jangan balik sini lagi.”
Merah padam muka Pak Ali menahan marah. Ketika itu semakin kecil sahaja Aliff kelihatan.
“Tak kira ayah. Ayah ni pentingkan diri saja. Ayah lupa apa jadi pada Along? Along mati pun sebab ayah.”
Panggggg, sedas singgah ke pipi Aliff. Anaknya berlari terus masuk ke biliknya.
Tangan kirinya terasa kebas, hati terasa sayu. Sejak 25 tahun lepas belum pernah tangan itu singgah ke tubuh anaknya apatah lagi mukanya.
Sejak Asraf, anak sulungnya meninggal dunia, Aliff saja tempat dia menaruh harapan. Dia tidak punya sesiapa lagi. Tanpa Aliff siapa lagi yang mahu diwariskan bendang itu. Walaupun sekangkang kera tanah itu sajalah harta mereka.
Kadang-kadang dia merasa terlalu berkeras dengan Aliff. Setiap kali memandang wajah Aliff dia membayangkan dirinya. Dia mahu Aliff menjadi sepertinya.
Dua puluh tahun lalu, dia mengusung isteri dan dua anaknya meninggalkan hutan konkrit yang penuh mimpi. Masih terngiang kata arwah bapanya, “Kalau hang tak balik, sapa lagi nak buat bendang ini, Ali?
Kadang-kadang terdetik juga hatinya, kalau dia masih menyarung uniform askar itu mungkin dia sudah berpangkat besar hari ini dan mampu memberikan semua kemewahan untuk keluarganya. Namun demi wasiat ayahnya, dia kembali juga ke Kampung Sendora.
“Abang, minum. Abang nak makan nasi saya ambilkan?” Mak Milah mencelah lamunan Pak Ali yang tersandar keletihan di tiang beranda rumah mereka.
“Takpa. Biar dulu.”
“Ini Milah, RM5,000, separuh simpan, separuh bagi Aliff buat beli motor baru. Motor lama pun dah laeh tu,” kata Pak Ali menghulur segulung wang kertas RM50 yang diikat dengan gelang getah.
“Baiklah bang. Nanti saya bagi. Sukalah dia nanti,” Mak Milah tersenyum.
“Abang tak mahu beli apa-apa ke?” Tersentak Pak Ali mendengarnya.
“Tak apalah Milah abang tunggu nantilah. Abang minta maaf tak dapat nak tebus lagi rantai Milah tu. Padi tak jadi musim ini, habis makan ulat, tangkai reput. Banyak kena potong. Separuh dah bayar hutang pada tauke Ah Seng.”
Mak Milah diam sahaja dan tersenyum. Ditatap wajah suaminya itu. Sayu. Uban sudah memutih pada rambutnya. Lelaki kesayangannya itu nampak lebih tua daripada usianya. Pada usia 60 tahun itu Pak Aliff tentu nampak lebih tampan jika masih bergelar orang Kuala Lumpur. Dia tahu Pak Alif kuat bekerja. Kerja keras itu meragut usianya.
“Milah buat kopi ya bang?” Wanita itu cuba memujuknya. Pak Ali hanya tersenyum.
Rokok daun tembakau tiga itu disedut perlahan-lahan. Sakit pula dikenangkan kata-kata tauke Ah Seng tadi.
“Tauke, bagi lebih lah. Hutang nanti aku bayar musim depan. Aliff nak beli motor.
“Mana boleh, Pak Ali. Kalau simpan nanti bunga lagi banyak. Mahukah? Macam ini lah kalau Pak Ali tak larat buat bendang ini jual sama saya. Apa macam? Habis cerita. Pak Ali sudah tua ma,” pujuk tauke Cina itu sambil tersengih menampakkan gigi kuningnya. Itu bukan kali pertama Ah Seng memujuk Pak Ali.
“Sudahlah tauke, mai sini duit itu,” sergah Pak Ali berlalu dari situ. Dia tahu kalau lama lagi tentu berperang besar mereka.
Pak Ali tahu tidak ada apa yang boleh dilakukan. Petani sepertinya tidak akan terlepas daripada cengkaman tauke padi seperti Ah Seng.
Bukan dia seorang terkena tetapi itulah cara tauke Cina seperti Ah Seng menekan mereka. Namun untuk menyerah kalah dan membiarkan tanah-tanah bendang ini jatuh ke tangannya tidak sama sekali.
Lamunan Pak Ali di beranda rumah kayu mereka itu tersentak lagi. Aliff tiba-tiba muncul. Sengaja menginjak-ginjak lantai kayu yang hampir reput itu tanda protes kepada ayahnya.
“Adik, ayah bagi duit padi esok bolehlah tengok motor baru di pekan tu kan,” Mak Milah mengekori dari belakang. Di tangan membawa secawan kopi. Dia cuma berharap berita itu meredakan kemarahan Aliff terhadap ayahnya.
Terhenti langkah pemuda itu. Memang sudah lama mengidamkan motosikal baharu. Honda Cub itu hampir seusia dengannya. Asyik rosak sahaja.
Fikirnya, mahu tayang motosikal baharu itu kepada Suri nanti.
“Baik mak,” balas Aliff. Panjang senyumnya.
Ditoleh ke arah Pak Ali yang masih ralit menyedut rokok daunnya. Lelaki tua ini tangannya sudah bergetar, kedut di dahi makin dalam. “Maafkan, adik, ayah,” Aliff hanya mampu bisik itu dalam hatinya.
“Mak, ayah, orang ke bendang dulu.” Sudah lama pulang ke Kedah ini loghat bandarnya kadangkala tersembul juga. Kadang-kadang hati Aliff berdetik. Kalau mereka sekeluarga masih menetap di Kuala Lumpur tentu hidup mereka lebih baik. Tentu Suri akan menerima cintanya. Tentu dia akan digelar lelaki tinggi, hitam manis dan kacak. Pujaan ramai anak gadis kampung itu.
“Hati-hati adik kalau hujan balik cepat. Nanti tolong ambilkan cangkul ayah di parit gila itu. Lupa bawa balik tadi,” pesan Pak Ali.
Aliff sekadar mengangguk. Dia kembali menatap wajah kedua-dua orang tuanya itu. Entah kenapa hatinya tiba-tiba berbungkus pilu. Walaupun kecewa kerana hasratnya untuk ke Pulau Pinang tidak kesampaian. Aliff semakin sedar. Mungkin itulah hidupnya. Seperti Pak Ali, dia perlu berkorban.
Pak Ali memandang dari jauh Aliff menunggang motosikalnya itu berlalu sampai hilang.
Tidak sekelumit pun benci di hatinya untuk Aliff kerana dia sajalah yang tinggal sejak Asraf meninggal dunia, 15 tahun lepas.
Jarak usia Asraf dan Aliff cuma lima tahun. Sampai bila pun Pak Ali tak akan lupa saat dia menemukan Asraf di dasar sungai yang terletak tidak jauh dari bendang mereka itu. Badan Asraf sejuk dan bibir yang sudah kebiruan. Dia tahu salahnya, Asraf yang tidak berapa sihat dipaksanya ke bendang. Asraf tergelincir ketika mahu mencuci kaki di tebing sungai yang membuak airnya setelah hujan lebat sebelah malam. Mungkin betul kata Aliff, dia yang menyebabkan Asraf mati.
Pang!
Berdentum kedengaran suara dari awan memecah keheningan Kampung Sendora. Berkali-kali.
Pang! Pang!
Pancaran cahaya umpama kilauan pedang itu terus mengejutkan Pak Ali. Tiba-tiba hatinya berdebar. Awan hitam mula menungkup langit.
“Milah nak hujan, mana Aliff tak balik lagi?” hatinya sudah risau.
“Ambil topi abang nak tengok dia,”
Mak Milah hanya menuruti.
“Ini abang.” Namun belum sempat tangan Ali menyambutnya.
“Pak Ali, Pak Ali, Aliff…” cemas kawan Aliff dengan nafas tercungap-cungap berlari mendekati rumah pusaka itu.
“Aliff… Pak Ali… Aliff… Aliff…,” Kamal belum mampu berkata-kata.
“Kenapa Kamal? Kenapa?”
“Aliff, Aliff kena sambar kilat Pak Ali… tang parit gila,” teriak Kamal.
“Abang! Abang! Tunggu,” jerit Mak Milah. Wanita itu terasa badannya seakan melayang. Kaki tersandung di beranda rumah kayu itu. Terduduk. Terasa mahu pitam.
Tidak dihiraukan panggilan itu. Kaki Pak Ali semakin cerdas, berkaki ayam berlari laju ke arah parit gila yang kurang sebatu dari rumah mereka.
Semakin dekat, semakin laju jantungnya berdengup. Melihat sekujur tubuh Aliff tertiarap di tebing parit gila itu dengan tangan yang masih memegang erat cangkulnya, kaki Pak Ali tak mampu bergerak lagi. Lembik.
“Adik,” rintihnya.
Awan hitam yang bergantungan mula menitiskan hujan. Parit gila yang tadi tenang, berkocak kembali. – MINGGUAN MALAYSIA