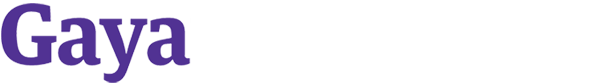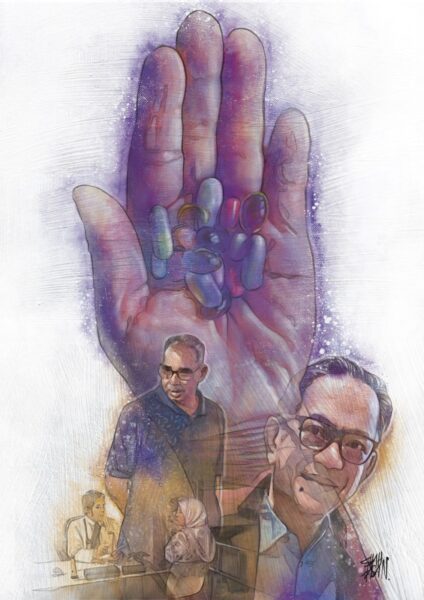cerpen
Karya Ilya Alias
ANAK sungai di kawasan ini paling panjang, lebar dan dalam, itu kata mereka. Aku tidak bercadang hendak meneruskan perjalanan ke destinasi tujuan kerana keadaan gelita dengan jalannya yang berbengkang-bengkok.
Pos terakhir sebelum tiba di kawasan Long Panai adalah Marudi. Sekarang aku berada di tengah-tengah jalan antara Marudi dan Long Panai. Kalau diikutkan kata mereka, perjalanan ini hanya mengambil masa kira-kira dua jam setengah menggunakan jalan darat, tetapi disebabkan hujan serta kekangan jalan yang buruk, perjalananku lewat ketinggalan.
Aku menoleh ke sekeliling, sunyi. Hanya kedengaran suara hutan serta deru sungai. Aku mencari tempat yang sesuai untuk memparkirkan kereta. Nampaknya, telahan awalku untuk tidak bermalam di dalam hutan tersasar jauh walaupun bertolak dari Marudi pada pukul dua petang.
Aku tidak mendirikan khemah sebaliknya hanya menggantung buaian di antara dua pokok belian yang kukuh dan renjong ke atas. Langit lapang dengan gugusan bintang mengisi seluruh ruang.
Jalan ke pedalaman memang mendebarkan tanpa turapan tar serta akar-akar banir besar liar yang merayap sehingga ke tengah jalan.
Semasa dalam perjalanan, beberapa kali kepalaku terhantuk pada pintu kereta kerana melanggar bonggol tanah dan kayu ketika memandu. Aku cuba menyelesakan badan di atas buaian, memandang tompok-tompok berlian di langit.
Tubuhku terasa penat sekali, namun mataku tidak mahu pejam. Debur air tidak jauh dari tempatku berehat menggetarkan dada. Sebelum memulakan perjalanan di kawasan pedalaman, aku sudah diberitakan tentang keganasan Sang Bedal.
Namun, atas dasar kerja untuk melihat sendiri tapak yang dicadangkan sebagai empangan terbesar di Malaysia, aku setuju untuk melakukan ekspedisi ini, sendirian.
Kocakan air kian ganas, aku membesarkan anak mata. Awan perlahan-lahan menutup bulan sehingga malam berubah gelita. Aku menoleh ke arah unggun api yang masih menyala. Aku kaget apabila bahagian bawah buaian seperti direngkuh sesuatu.
Kelihatan seekor buaya membuka mulutnya luas-luas di bawah buaian. Awan yang perlahan-lahan bergerak pergi, memberikan ruang untukku melihat seekor lagi buaya benar-benar di hadapanku! Buaya tembaga dengan kulit yang keras, tebal dan panjang sekitar 30 meter menganga luas, menampakkan rahangnya yang besar dan tajam. Aku terkedu membisu.
“Kami sememangnya sudah dapat menghidu kedatanganmu ke sini,” ujar buaya tua tersebut dengan pandangan mata yang tajam dan bersinar.
“Kau..Kau dapat bercakap, dan aku dapat memahaminya?” Aku semakin keliru.
“Benar. Usah khuatir kerana aku tidak berselera untuk membahammu.”
“Justeru, mengapa kau ke mari?” Aku mengerling ke arah kereta yang terletak satu meter dariku.
Kemudian, pandanganku terarah pada unggun api. Seekor buaya dengan saiz yang lebih kecil berkawal berdekatan dengan unggun api tersebut.
Jaring buaianku di tarik ke bawah, satu bahagian hampir putus. Aku naik jelik melihat rahang buaya yang ternganga berdekatan punggungku. Buaya tua tersebut merangkak ke hadapan, menghampiriku lebih dekat. Nafasku berombak laju.
“Pastinya kau tahu akan sengketaku dengan manusia, bukan?”
Aku mengangguk.
“Segala tanggapan buruk yang dilemparkan kepada kami adalah dusta semata. Kami bukan begitu. Bahkan kami tidak ingin menjamah tubuh manusia.”
Aku tidak berkata apa-apa. Bau hamis dari rahangnya sangat memualkan. Aku menekup mulut, berusaha menapis udara busuk yang masuk dengan jemari yang gemuk, tetapi gagal.
Selut yang memenuhi bahagian belakang buaya-buaya tersebut juga sangat menggelikan. Bau air selut yang hitam pekat dan hanyir terus menguasai seluruh atmosfera.
“Aku tahu bahawa kau akan ke sini, kerana itulah kami bersedia untuk bertemu kau. Kami mahu khabarkan kepadamu siapa yang sebenarnya binatang…”
“Teruskan, buaya tua…”
Aku terus mendengar dengan teliti. Sedikit demi sedikit, ketakutanku pudar, diganti dengan rasa kasihan apabila melihat pandangan mata buaya tua itu yang redup dan sayu.
Anak matanya seolah-olah menceritakan keperitan yang dilalui oleh mereka selama ini.
Di sekeliling matanya, terdapat kesan koyakan sepanjang satu inci, barangkali terkena besi yang jatuh ke dalam sungai. Bahagian belakang badannya juga calar-calar.
Di antara jari-jarinya juga koyak dan terdapat kesan darah yang masih segar. Sekiranya situasi tersebut terjadi pada diriku, pasti aku sudah terlantar di atas katil hospital selama berminggu-minggu akibat jangkitan yang serius.
“Sudah lama kami terlonta-lonta dalam kesusahan. Perit untuk kami mencari makan kerana rumah kami bagaikan takungan air yang sentiasa berubah. Kami tidak lagi bebas untuk bermewah dalam kehidupan ini kerana manusia seringkali melupakan budi.”
“Maksudmu?”
“Ah, benar sekali telahanku. Kau memang terlalu naïf tentang hidup. Manusia hanya memburu pembangunan dan kemegahan.”
Ada butir-butir halus yang muncul dari kelopak mata tuanya sehingga mengalir menjadi air mata dan aku terjunam ke dalam emosi buaya tua itu.
“Bagaimana dengan sisa manusia yang mereka jumpa terdampar di tebing sungai ini beberapa hari lepas?”
Mindaku ligat mengimbau kisah mayat seorang lelaki tanpa lengan yang dijumpai terdampar di tebing sungai selepas hilang daripada mencari udang galah beberapa minggu lalu. Kisah itu juga diulang cerita oleh dua lelaki tempatan yang aku temui ketika berehat seketika di salah sebuah warung di Marudi.
“Ah, sekiranya mayat tersebut boleh muncul dan kembali berkata-kata, pasti dia akan katakan penyesalan yang amat sangat kerana menembak keturunan kami tanpa peri kemanusiaan!”
Aku terus membisu. Membiarkan angin malam menampar wajah serta bising dengung serangga yang menghurung kepala.
“Apa mahumu datang kepadaku malam ini?”
Buaya tua itu membuka mulutnya lebih luas, diikuti oleh buaya-buaya lain. Sekali lagi, nafasnya tersekat. Dia cuba menjadi budiman, berpura-pura udara yang disedutnya baik-baik sahaja.
“Kami adalah spesis pemula dunia. Buktinya, kami wujud pada 83.5 juta tahun yang lalu. Adalah menjadi sesuatu yang kesal apabila hidup kami bergelumang dengan cacian dan tohmahan mereka.
“Sekarang, kawanan kami kian kecil saiznya seiring dengan dunia yang semakin sempit usia. Sungai kami kian sempit, tetap kami juga yang dipersalahkan atas segala kematian manusia yang terjadi di sungai ini.”
Aku terus membiarkan buaya tua itu bersuara sambil melihat ekornya yang mampat isi tergodek-godek mengusik ranting-ranting kering di atas tanah.
“Terus, apa yang kau mahu aku lakukan?” Malam kian larut dan perbualan kami nampaknya belum ada tanda-tanda akan berakhir.
“Aku mahu kau balas dendam pada koloni manusia yang menjatuhkan kami.”
Keningku bertaut. Terasa angin malam seakan menamparku lebih kuat dan ganas. Api pada unggun hampir malap. Bara-bara yang merah hitam dilekap api sahaja yang masih bersisa. Aku kian runsing.
“Bagaimana?” Sengaja aku menduga.
Wajah buaya tua yang redup bertukar nada. Dari sinar matanya, aku dapat lihat api kemarahan yang kian menggunung.
“Hutang darah dibalas darah, hutan budi bawa ke mati.”
“Ah, buaya! Egomu lebih besar daripada Amerika!”
“Keturunanku adalah pewaris dunia paling tua, dan wajib dihormati.” Dengus buaya tua itu jelas kedengaran.
Perbualan kami terhenti apabila melihat cahaya pacuan empat roda samar-samar mendekati. Dua orang lelaki turun dari kenderaan tersebut dengan senapang terhunus panjang.
“Aku tahu perkara ini akan terjadi,” garau ujaran lelaki tersebut.
Aku kenal mereka, lelaki-lelaki yang garang bercerita tentang keangkuhan buaya-buaya ini mengunyah, membaham dan meludahkan tulang-tulang mangsa di warung siang tadi.
Bahkan kata mereka, sengaja buaya-buaya ini membuang maruah manusia dengan membiarkan sedikit sisa badan manusia hanyut dan terapung sehingga dijumpai orang.
“Apa yang mereka kisahkan kepadamu?” Lelaki tersebut menghampiri buaya yang mengawal di belakangnya. Senapang masih terhunus tepat ke kepala buaya tersebut.
Seorang lagi lelaki juga melakukan yang sama. Buaya tersebut membuka rahangnya dengan lebih luas, mencabar muncung halus senapang yang ditalakan ke arahnya.
“Mereka kisahkan perkara yang kau sendiri tahu,” ujarku.
Udara yang keluar masuk dari paru-paruku terasa berat.
“Kau dengar apa yang aku katakan tadi, inilah masanya,” kasar suara buaya tua. Aku terus membatu.
“Hei, orang luar…Usah kau peduli apa kata haiwan-haiwan ini. Mereka adalah pemakan bangkai seumur hidup.”
Nganga buaya-buaya di hadapanku kian besar. Api kemarahan mereka membuak-buak.
“Kau tunggu dan lihat.” Lelaki tadi ke belakang kereta. Mengeluarkan bangkai kambing dengan aroma yang menyakitkan hidung.
Aku menekup mulut, hampir termuntah melihat bangkai kambing yang diletakkan di tengah-tengah kawanan buaya tersebut. Perut kambing tersebut kembung dan sebahagian badannya berulat sakan.
Melalui sinaran rembulan yang dipinjamkan, aku lihat ulat-ulat serta renga jatuh apabila kambing tersebut berada di udara. Bagaikan besi yang ditarik kersani, buaya-buaya tersebut tidak mampu membendung diri lantas meratah bangkai kambing dengan lahap sambil berebut-rebut antara mereka.
Bangkai tersebut diratah, dikoyak serta ditelan bulat-bulat. Aku segera mengendurkan buaian perlahan-lahan, memijak tanah dan berdiri di sebelah lelaki yang lebih sasa tubuhnya.
“Lihat..”
Pandanganku tertancap pada buaya tua yang cuba melawan nafsunya untuk menikmati bangkai dengan rakus, namun kalah. Buaya tua tersebut melibas ekornya yang berat dan padat, mendominasi seluruh bangkai sendirian.
“Mereka adalah pemakan bangkai.” Lelaki sasa tersebut mengeluarkan senapang, menghunusnya betul-betul pada bahagian kepala buaya tua yang ralit meratah bangkai.
Aku segera menghampirinya, menghalang lelaki tersebut sambil berkata, “Usah jadi seperti api yang kononnya memberikan kehidupan baru kepada bumi.” – Mingguan Malaysia