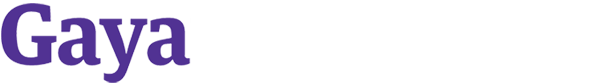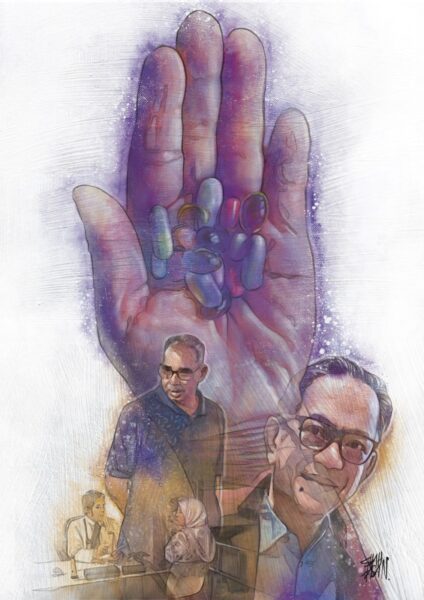CERPEN
Namaku Emmanual. Nama yang telah termaktub semenjak hari pertama aku dilahirkan di hospital De Lar Motte, pinggir kota Paris yang tersergam Eiffel Tower yang menakjubkan genap dua dekad silam. Dunia remaja yang ku lalui penuh dengan seribu keindahan dan keseronokan sebagai anak muda Eropah yang menganuti fahaman sekularisme dan liberalisme.
Bagiku, hidup adalah sebuah kebebasan asasi yang tidak boleh disekat oleh apa jua nilai dan fahaman tradisi silam. Manusia diberi naluri untuk melampiaskan segala keinginan dan nafsu. Akal adalah hukum tertinggi kerana di situ lahirnya logik dan hak asasi manusia. Kebenaran tidak lebih hanyalah jawapan kepada manusia dangkal yang sering tewas dalam perebutan duniawi.
Argh, perempuan itu entah dari mana muncul cuba menyihirku dengan pelbagai ideologi dan fahaman kolot dan ketinggalan zaman. Perempuan muda berlitup separuh wajah mahu dikenali dengan panggilan Siti Maryam. Dia satu-satunya muslimah di dalam kelas kami yang cepat merah padam wajahnya tatkala aku berhujah di hadapan kelas bahawa seni adalah saluran kebebasan manusia untuk menzahirkan karya.
“Barat selalu menjadikan seni sebagai medan untuk mengkritik sesiapa yang tidak sehaluan. Seni yang indah dan mulus sering ditafsirkan sebagai luahan fundamental dan melampau termasuk mencerca manusia lain.”
Suaranya lantang dan tegas bagaikan seorang politikus yang berani.
Ketika mendaftarkan diri sebagai siswa di pusat pengajian seni di pinggir kota Paris sepurnama lalu kelibat gadis berjilbab sutera Istanbul itu mula mencuri pandanganku. Dengan protes-protes kerasnya tentang seni dan sastera. Ada sesuatu yang ku rasa berbeza saat berhujah dengan gadis yang terserlah dengan akhlak dan adab itu di hadapan kelas seni abstrak.
“Seni itu anugerah Tuhan terindah. Bukan untuk mengkritik kebenaran dan Tuhan tetapi untuk menzahirkan rasa cinta terhadap kehidupan dan kemanusiaan.”
Dia memberi pendapat tatkala semua pelajar di kamar berpetak itu diminta untuk berkongsi pendapat tentang seni halus yang bersifat teori. Pandangan kami bertentang tatkala ku rasakan dia cuba merendahkan pandangan sebahagian daripada kami.
“Apa buktinya?”
Aku membalas hujahnya. Terasa geram sambil mengacip bibir dengan rasa marah. Wajah bujur sirih itu begitu tenang seakan tidak pernah gentar dengan renungan 30 biji mata siswa-siswi Barat di kelas yang membentuk sebuah galeri klasik ini.
“Saya tidak sekali-kali ingin bertelingkah atau berselisih faham akan tetapi sekadar ingin menyuarakan pendapat. Bagi saya hujah Charlie Hebdo tentang seni satira adalah silap dan keterlaluan. Karikatur bukan alat propaganda untuk membunuh jiwa manusia yang dimusuhi.”
Suara itu menyinggahi gegendang telingaku.
“Aku tidak ingin mendengar pendapat jelekmu, duhai Siti Maryam. Kau tidak perlu membawa ideologi kolotmu dari dunia timur di bumi Eropah ini. Seni anutanmu itu hanyalah tahyul dan penuh dengan khayalan kosong.”
Aku mengangkat suara sambil tepukan kuat bergema dari setiap penjuru.
Kelas seni abstrak petang itu terpaksa ditamatkan lebih awal apabila beberapa pelajar lain mula mengeluarkan kata-kata biadab dan provokasi kaum terhadap Siti Maryam. Ada yang melemparkan tohmahan dan cerca hingga kelas bertukar menjadi drama panas. Gadis muslimah itu menangis teresak-esak lalu berlari keluar meninggalkan kelas seni Leonardo Da Vinci itu di tingkat dua.
Petang redup itu yang didinginkan dengan cucuran salji dari langit berubah menjadi pentas hangat dengan cerita-cerita yang cepat merebak. Wajah gadis Melayu berkelubung itu mula meniti percakapan ramai orang. Gadis Melayu yang kaya dengan adab.
“Seni sepatutnya menyatukan kita untuk menentang keganasan dan perseteruan. Sayang, kita memilih seni keras, rakus dan menyongsang arah.”
Siti Maryam masih tidak berpuas hati. Suara lunaknya di dalam kelas gagal menjinakkan hati dan jiwaku dan rakan-rakan lain.
“Kami percaya kepada hak asasi di dalam dunia seni. Justeru, tiada pelanggaran moral dalam dunia karikatur dan satira oleh pemuja seni barat. Manusia bebas untuk mencorakkan apa sahaja karya termasuk memperlekeh fahaman kepercayaan lain..”
Aku tegas mempertahankan ideologi yang ku anuti.
“Ya, dahulu Geert Wilders, si politikus Belanda juga sependapat denganmu, Emmanual. Dia menganggap seni itu kebebasan mutlak untuk mencerca orang lain. Akhirnya, Tuhan menurunkan hidayah lalu dia memilih untuk bersama kebenaran yang pernah ditentangnya.”
Aku terdiam. Lidah seperti kelu untuk membalas kata-katanya. Perempuan itu terlalu licik dengan lenggok bicara yang mematahkan setiap hujah akal kami. Aku seperti terperangkap dengan dalil dan realiti yang dibentangkannya.
“Kau tahu apa yang berlaku kepada Salam Rushdie – Satanic Verses hasil seni daripada novelis jelek itu mencemar seluruh dunia dengan protes dan kebencian.
“Karyanya diiktiraf dan mendapat sanjungan Barat dan Eropah akan tetapi hidupnya diselubungi sunyi dan tersembunyi. Lelaki karyawan itu menjadi pelarian seumur hidup dan hilang nikmat sebagai manusia yang bebas menikmati kehidupan. Dunianya terpenjara bagaikan sangkar yang menutup segala keindahan.Kesilapannya hanya satu – menggunakan kalam dan tinta seni untuk menjatuhkan maruah pihak lain.”
Hujan bulan Julai di kota Paris menjadikan lanskap Eropah itu dibasahi takungan air di merata tempat. Dari jauh Eiffel Tower tersergam mencakar langit dengan kerlipan neon yang memacari setiap ruang dan tempat. Musim bunga adalah saat terindah dinanti-nantikan. Lilium, primerose apatah lagi tulip indah memenuhi setiap taman dan bahu jalanan. Semerbak bau lavender di taman klasik Jardin du Lexembourg kerapkali memberikan seribu ilham kepadaku untuk menghasilkan karya lukisan . Aku teringin menjadi pelapis kepada seniman agung barat – Leonardo Da Vicci yang terkenal dengan karya imaginatinya Monalisa.
Dari tingkap kaca jendela apartmen yang separuh terbuka, aku memerhatikan pemandangan sebu dari langit. Bintang-bintang di puncak angkasa berselerak dengn kerlipan halus yang serba mulus. Dari kotak emelku pada skrin komputer riba tiba-tiba muncul tulisan kecil daripada seseorang yang cukup ku kenali. Kata-kata itu kuamati berulangkali dengan perasaan aneh dan luar biasa.
Saudara Emmanual yang kuhormati,
Kukira tidak salah untuk kita berkongsi pendapat di ruang kecil media komunikasi ini. Aku sangat menghargai pendapatmu tentang seni di dalam kelas kita. Seni yang serba indah, halus dan absurd itu sepatutnya mengakrabkan kita dengan ukhuwah dan silaturrahim. Aku pecinta seni dari timur dan kau yang sedang berkira-kira bergelar karyawan seni kelahiran barat seharusnya menyanjungi seni sebagai anugerah terindah dari Tuhan. Sayangnya, kita memilih seni sebagai picu untuk melepaskan api amarah dan kebencian.Seni menjadi alat untuk melontarkan peluru permusuhan sehingga ramai yang terluka jiwa dan emosi. Kembalilah kepada fitrah untuk menghiaskan warna dan lakaran seni dengan penuh ketulusan dan keharmonian. Aku sangat menghargai seni yang kau perjuangkan. Samalah dengan kekagumanku terhadap seniman Leonardo Da Vinci, Claude Monet, Pierre Agustre, Vincent Van Gogh dan ramai lagi.
Semoga seni akan menghadiahkan kita rasa cinta paling tulus di kalbu yang kudus.
Siti Maryam.
Ada sesuatu yang ku rasakan mengalir di lubuk perasaan ini. Perasaan aneh dan luar biasa saat selesai menikmati kata-kata terindah itu. Gadis bermata bundar dengan senyum manis yang sentiasa terukir pada wajah berkelubung jilbab itu seperti melakari kalbuku dengan limpahan seni yang serba asing. Ungkapan tulisan itu bagaikan hujanan penawar yang jatuh luruh mendambakan perasaan kecil ini. Perasaan yang sekian lama dicucuh bara dendam dan kebencian terhadap perawan muslimah itu.
Eiffel Tower terus terpacak di situ saat aku memilih untuk menutup jendela kaca yang ternganga. Langit melimpahkan cahaya kejora dengan gumpalan awan putih yang berarak lesu. Mataku masih terpacak pada gugusan bebintang yang terapung di langit kirmizi. Lakaran seni paling agung ciptaan Tuhan yang Maha Pencipta. Aku mendongak ke puncak bima sakti saat tiba-tiba hujan berluruhan jatuh bagaikan manik-manik jernih yang bertitisan.
Tangisankah itu? Ku sapu manik-manik kecil yang mula mengalir di raut wajahku yang terasa sebu. Ingatan terhadap perempuan pecinta seni itu kembali muncul di benak perasaanku. Perasaan yang aneh dan misteri. Lantunan suaranya terngiang-ngiang muncul di cuping gegendangku. Suara yang lantang memperjuangkan ekspresi seni yang luhur, tulus tanpa keladak-keladak hitam propaganda.
“Islam datang membawa seni yang luhur, saksama dan mengasyikkan. Bukan seperti mana tuduhan sesetengah pihak. Kami menolak fanatik dan keganasan. Ekstremisme tidak pernah wujud dalam kamus hidup kami.”
Suara itu muncul entah untuk kali yang keberapa.
“Bukankah moyangmu – pendeta seni Herbert Read pernah berkata bahawa seni adalah satu usaha untuk mencipta bentuk-bentuk karya yang menyenangkan nurani dan fitrah manusiawi.Lewat bukunya Meaning of Art telah kutelaah berulangkali betapa seniman dan karyawan barat terdahulu juga sependapat dengan kami.”
Pertanyaan itu berdengung-dengung masuk ke liang telingaku sebelum lenyap dan hilang. Aku terkesima. Fikiranku kosong. Puluhan teori dan mazhab seni yang pernah kuhafaz semenjak di kolej lagi bagaikan kerikil-kerikil keras yang mencucuk-cucuk dada kecil ini. Benarkah seni bebas mengkritik Tuhan dan kebenaran? Apakah seni lakaran berhak menjatuhkan prestij dan maruah insan lain yang berperwatakan mulia? Bukankah seni anutan Barat lebih mementingkan keindahan semata tanpa memperdulikan moral dan akhlak?
Persoalan demi persoalan bermonolog dalam benak fikirku. Aku seperti berada di dua persimpangan jalan yang berliku dan berkabus. Sukar membuat pertimbangan walau berkali-kali aku memilih untuk merasionalkan akal dan jiwa demi menjejak jawapan.
Namaku bukan lagi Emmanual. Emmanual yang pernah ku bangga-banggakan kerana terpilih sebagai tokoh pelajar paling berbakat dalam menghasilkan calitan warna. Emmanual yang gah mencipta nama dengan lakaran-lakaran lukisan abstrak yang berpotensi besar. Aku benci dengan nama itu. Nama yang membuatkan Siti Maryam dan sebahagian pelajar berdemonstrasi di sepanjang jalan Notre Damn yang sesak. Pada poster kecil terjulang ditangan mereka tertulis luahan kecewa dan marah untuk seorang politikus bernama Emmanual. Puncanya hanya satu – lelaki penguasa itu telah mengguris hati sebahagian pelajar muslim dengan ucapan perkauman yang berbaur provokasi. Semuanya bermula daripada lakaran-lakaran seni jelek membentuk wajah karikatur insan agung yang membawa nur wahyu untuk umat akhir zaman.
“Namaku bukan lagi Emmanual.”
Siti Maryam yang lengkap berjubah kelabu dengan lilitan kain hijau di kepalanya berpaling menatap wajahku lama-lama. Kedua-dua matanya terbeliak besar seakan tidak percaya.
‘Siapa sebenarnya dirimu sekarang?”
Dia bersoal ingin mengetahui. Wajahnya serius.
“Aku tidak mahu berkongsi nama dengan penguasa berhati hitam dan songsang itu.”
Kuc uba meyakinkan dirinya. Raut wajahnya tiba-tiba berubah saat lidahnya melunurkan ungkap Alhamdulillah serta bertasbih panjang-panjang.
“Aku sedang mencari seni paling indah di dalam fitrah diri ini. Seni anugerah Maha Pencipta. Semoga seni itu mendidik seluruh inderaku untuk melahirkan karya-karya seni tulus, kudus dan penuh dengan keindahan hakiki.” – Mingguan Malaysia